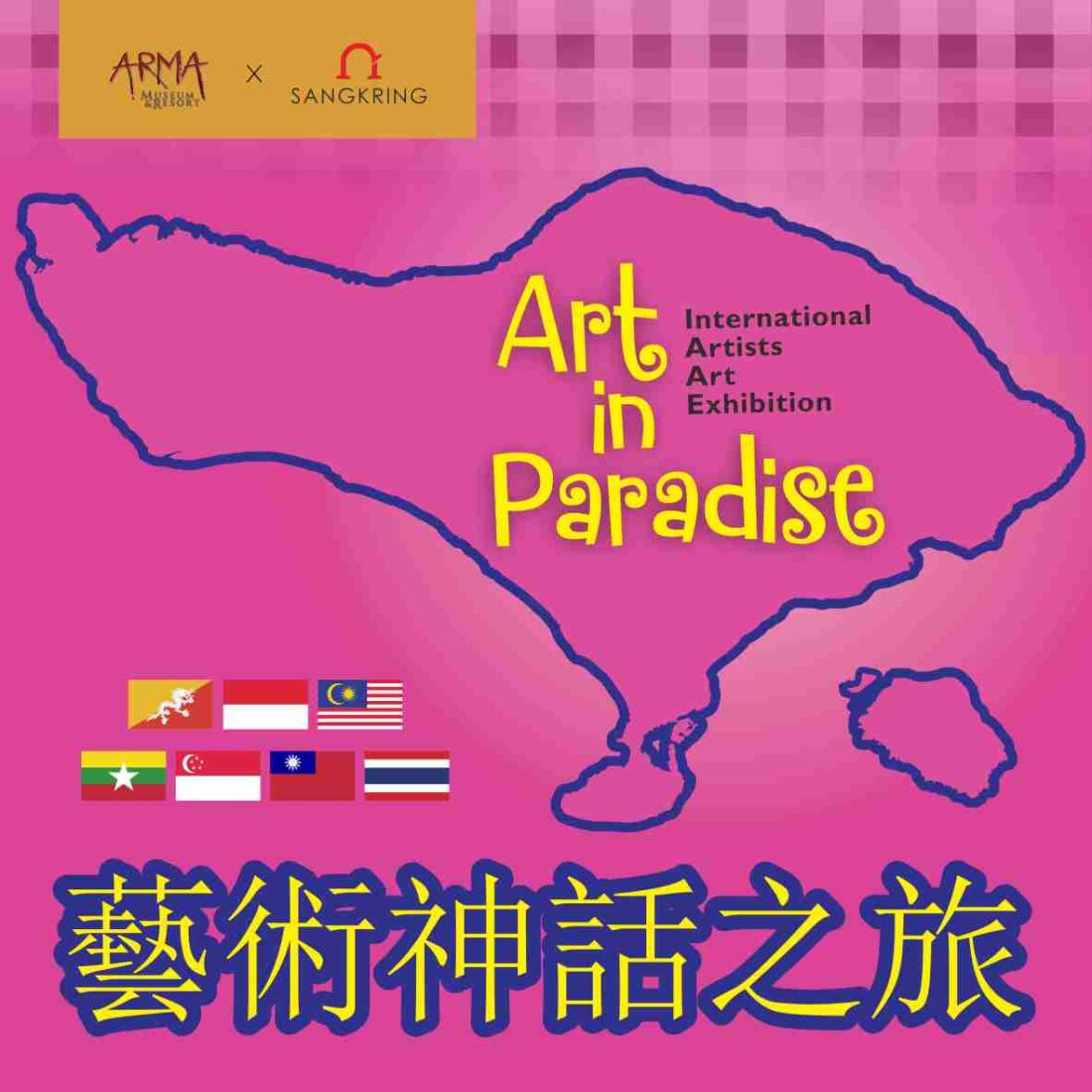[Exhibition] Fatamorgana – I Putu Bonuz Sudiana
[Exhibition] Lelampah – Putu Sutawijaya
Link E-Katalog https://drive.google.com/file/d/17TiQHeImlBuLDeoH5R2udjgIMVAzOmDS/view
[Exhibition] SDI X SDI – Sanggar Dewata Indonesia
[Exhibition] Wayang Carangan – Nasirun
[ArtWork] Dona Prawita Arisuta – INFIN#8 YAA2023
Konsep berkarya :
Palimpsest secara literal adalah kertas (perkamen) yang pernah ditulis, kemudian ditimpa dengan tulisan baru, di mana tulisan lamanya belum terhapus sepenuhnya. Istilah “Palimpsest” dipilih untuk menggambarkan proses penanaman moral secara berulang dengan pendekatan cerita yang diceritakan secara berulang-ulang dengan semua embel-embelnya: penafsiran, perubahan konteks dan lingkungannya.
Cerita-cerita relief Jataka di Candi Sojiwan bukan khotbah moral; plot dan gaya penceritaannya tidak memberikan arahan moral yang verbalistis dan langsung; orang yang mendengarkan dan menceritakan ulang diberi kebebasan untuk menangkap keluasan nilai kebijaksanaan dalam setiap cerita. Apalagi cerita-cerita dalam relief Candi Sojiwan menggambarkan nuansa kehidupan yang sangat manusiawi bahwa kebaikan bukan satu-satunya isi dari kehidupan. Kebaikan bukan suatu yang sudah ada pada setiap orang, tapi sebuah perjuangan yang lurus, di mana kadang kebaikan kalah oleh kejahatan, dan kemudian setelah proses panjang kebaikan diraih kembali.
Karya adaptasi terhadap relief Candi Sojiwan ini menegaskan efektivitas cerita dan posisi cerita sebagai wadah pengajaran dan pendidikan moral dalam kehidupan, terutama bagi anak-anak.
Cerita relief Candi Sojiwan memiliki aspek pengajaran dan pendidikan moral yang merupakan pengembangan dari sepuluh unsur Paramitha dalam ajaran Budha. Diantaranya :
- Relief kera dan buaya memiliki aspek pelajaran tentang kelicikan yang dibayar dengan kelicikan pula; Semua tindakan sebaiknya berdasarkan pada pertimbangan akal pikiran; Ukuran dan bentuk fisik bukan segalanya; Orang yang mau mendapatkan pencerahan tidak takut akan kesulitan dan memiliki keberanian menghadapi kesulitan.
- Relief singa dan lembu jantan: Saling mencurigai tanpa alasan berakibat tidak baik; Harus saling mempercayai dengan sahabat dan saudara; Membuang buruk-sangka; Perkataan tidak benar dan fitnah akan merusak persahabatan.
[will update soon]
[Exhibition] Yogya Annual Art #8 – INFIN#8 YAA2023
[Exhibition] Monotone, R. Wisnu. D
Rute Imajiner dan Sebuah Metafora
Siang itu, di dalam studionya, R. Wisnu. D bertutur tentang perjalanan-perjalanan yang pernah dia lakoni ke pelbagai tempat dan negeri, yang sekian tahun kemudian, yakni: pada saat ini menjelma sebagai rangkaian di atas kanvas. Kami coba mengamati lukisan-lukisan itu, sambil mendengarkan kisah lukisan cat minyak perjalanannya. Pikiran pun ikut mengembara, menjelajahi lokasi-lokasi yang mempertautkan praktik perjalanan, pengalaman estetik, dan penciptaan artistik.
Sepotong rute imajiner terpicu oleh sekian nama seniman-pelancong (traveler artists) yang mendadak sembul di benak: sejak dari Claude Monet, Vincent van Gogh, Edward Hopper, Affandi, Rusli, hingga Putu Sutawijaya. Fragmen-fragmen gagasan bersijingkat di tengah jalanan licin, lalu seperti semaunya saja singgah di ranah musikal, sosiologi tempat (sosiology of place), dan seterusnya, hingga pada akhirnya kembali ke dalam praktik perjalanan dan seni visual.
MonoTONe, sebagai tema pameran tunggal Wisnu di Sangkring Art Project, diadopsi dari ranah musikal mengacu kepada komposisi yang hanya menerapkan satu pitch atau tone. Musik minimalis, ambient, dan chanting adalah beberapa genre yang kerap mengeksplorasi monotoni dengan memaksimalkan repetisi dan kontras elemen-elemen musikal, entah ritme, harmoni, timbre, atau dinamik. Sebagai sebuah metafora, konsep ini sudah tak asing lagi bagi praktik seni visual. Di ranah ini monoTONe mengacu kepada warna atau hue tunggal. MonoTONe dalam sebuah lukisan, misalnya, bisa sangat potensial, memukau dan efektif, untuk menyugestikan suasana dan atmosfer yang dikehendaki. Meskipun begitu, secara umum kita menghindari monotoni lantaran kecemasan akan kebosanan, tetapi mengapa Wisnu justru menghampirinya?
Kita tahu bahwa preferensi pada lingkup warna yang terbatas, katakanlah pada warna “gelap” semata-mata, tetap mampu membuka kemungkinan kreatif dengan menyiasati elemen-elemen visual yang lain. Bisa disimak sebagian besar lukisan Wisnu yang cenderung gelap dan muram dari tiga lukisannya tentang Merapi, hanya satu yang relatif cerah. Akan tetapi, ternyata yang dimaksud sebagai monoTONe olehnya itu bukanlah (sekadar) perkara teknis. Wisnu sangat menyadari bahwa lukisan-lukisan yang dipamerkan sekali ini berorientasi pada suatu medan tematik tunggal, bahkan dalam genre tunggal pula, yakni lanskap. Bagaimanakah genre spesifik ini terbentuk? Apakah hubungannya dengan perjalanan, pelancongan?
Hasrat Perjalanan, Hasrat untuk melakukan perjalanan dan mengunjungi panorama tertentu adalah hasrat yang dikonstruksi secara kultural, bukan sesuatu yang alami. Hasrat kultural (cultural desire) ini, seturut sosiolog John Urry (1995), setidak-tidaknya terdorong oleh beberapa faktor. Yang pertama sudah jelas, yakni ketersediaan lokasi geografis yang dapat dikunjungi, sebagai hasil kemajuan fasilitas transportasi dan komunikasi.
Tak perlu berpanjang-panjang tentang ini, meski kita perlu mengingat pula bahwa tipe lanskap tertentu, semisal alam liar (wilderness), justru diminati orang lantaran kesulitan untuk dijangkau, minimnya fasilitas, serta sukarnya akses.
Faktor lain menyangkut pengelompokan sosial dengan orientasi estetik yang sesuai, misalkan terhadap gaya (style) tertentu atau jenis pemandangan (scenery) tertentu yang biasa disebut sebagai “lanskap”. Sehubungan dengan yang terakhir ini, apa yang barangkali bisa dinamakan “estetika alam” berpotensi sekaligus sebagai sumber penyegaran inspirasi dan kebangkitan rohani bagi kelompok atau kelas sosial tertentu.
jadi, bukan soal “keindahan” melulu. Katakanlah, sebagai satu contoh, danau yang tenang dianggap orang lebih mendamaikan hati, lebih meleramkan, ketimbang jenis pemandangan lain semisal padang pasir.
Dalam konteks pameran ini, muncul pertanyaan besar: sesungguhnya apa dan bagaimana basis sosial Wisnu sehingga dia memilih orientasi estetik sebagaimana terbaca dalam lukisan-lukisan lanskapnya?
Boleh jadi orientasinya itu dapat dipulangkan ke dalam latar budaya yang lebih umum, yang tersebar melalui pihak-pihak signifikan di tengah masyarakat yang lebih luas. Di dalam perkembangan genre lukisan pemandangan dan bentang alam, pasti terdapat figur-figur yang berpengaruh dan ikut memainkan peran yang tidak kecil dalam menyebar-luaskan preferensi terhadap tipe lanskap tertentu.
Bagi seorang seniman dan penyair Romantik, misalnya, menikmati alam adalah berarti berjalan kaki dalam kesendirian dan kesunyian, dengan suasana kontemplatif, demi menyembuhkan “luka batin” atau mencapai kesadaran spiritual. Maka, pertanyaan berikutnya: adakah sosok-sosok signifikan yang turut berperan atas preferensi Wisnu terhadap lanskap-lanskap tertentu?
Dan, pada akhirnya, mungkin kita perlu bertanya dan mempertanyakan pemahaman atas lanskap itu sendiri, sebagai faktor kunci dan sentral dalam menstrukturkan hasrat kultural atas pemandangan alam tertentu. Misalnya saja pengertian dan gagasan lanskap yang individualistis dan visual, praktik memandang (practice of looking) pribadi yang niscaya tidak pernah netral ― dengan memilah subjek (pihak yang memandang, mengamati) dan objek (pihak yang dipandang, diamati) melalui pengutamaan indra visual sang pengamat.
Jika memang konsepsi kita tentang sebuah lanskap pada dasarnya relatif bebas-insan, bangaimanakah prosesnya? Mengapa bisa terjadi demikian? Lanskap dan Dunia Simbolik Gagasan tentang lanskap pada mulanya merujuk kepada sebuah genre yang hendak menangkap pemandangan alam pedalaman/pedesaan (natural inland scenery), lalu mengerucut pada tapak daratan (track of land) tertentu yang ditatap dari sudut-pandang spesifik, dan pada akhirnya ia semata-mata merujuk kepada pemandangan alam (natural scenery) semisal hutan, ladang, pepohonan, gunung, atau pantai (baca: John Barrell, 1972). Dengan mencermati pergeseran pemahaman ini, dapat kita katakan bahwa lanskap bukanlah sekadar soal lingkungan fisik, melainkan sesuatu yang termediasi oleh proses apropriasi kultural.
Alam yang dipahami sebagai lanskap, jadinya, merupakan konstruksi sosial yang terkondisikan secara historis. Pada abad kesembilan belas, taruhlah, definisinya terhegemoni oleh dunia luar (eksternal) seperti pemandangan dan pandangan (views) yang diimbuhi sensasi-sensasi indrawi. Padahal, seabad sebelumnya, para bangsawan Eropa lebih mendefinisikannya dengan mengintegrasikan kelas bawah pekerja ke dalamnya, sebagai bagian terpadu dari lanskap itu sendiri, meskipun posisinya berjarak (in the distance) sebagai elemen visual yang nyaris tidak tampak. Dengan kata lain, kode genre yang khas ini bergeser senantiasa, entah dengan mengedepankan secara maksimal atau malah menentang dan menantangnya. Hal ini dapat kita bandingkan dengan lukisan-lukisam Wisnu yang di satu sisi bersetia terhadap kode, tetapi di sisi lain tampak kecenderungan beringsut darinya.
Telah lama pula kita paham bahwa genre lukisan lanskap sanggup menjangkau geografi imajiner, dunia mungkin (the possible world) yang berada di luar jangkauan nalar empiris. Bahkan di dalam lukisan-lukisan lanskap yang meminjam istilah dari Umberto Eco undercoding sekalipun, kerap kita temukan potensi tafsiriah yang luar biasa dalam menjangkau dunia simbolik (the symbolic world), yang sanggup menyugesti makna-makna emotif tertentu dan melampaui tampakan fisik semata, entah melalui metafora, ironi, hiperbola, dan sebagainya.
Sehampar padang rumput (prairie) di Montana, sebentang danau di dekat Dijon, Prancis, bahkan sepotong sungai di Kediri, menyodorkan makna emotif yang ngelangut. Sebatang pohon yang tegak sendiri menjadi metafora bagi kesendirian dan ketegaran; pun formasi awan di langit kelam menyuguhkan metafora yang dramatis.
Melalui lukisan-lukisan Wisnu, kita dapat meraih makna dan menikmati perjalanan ke dunia simbolik ini.
– Kris Budiman –