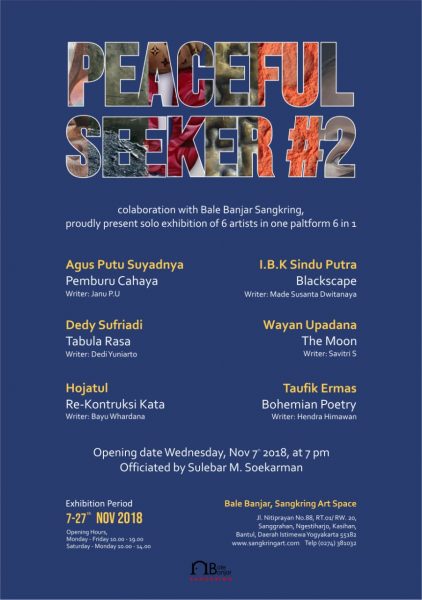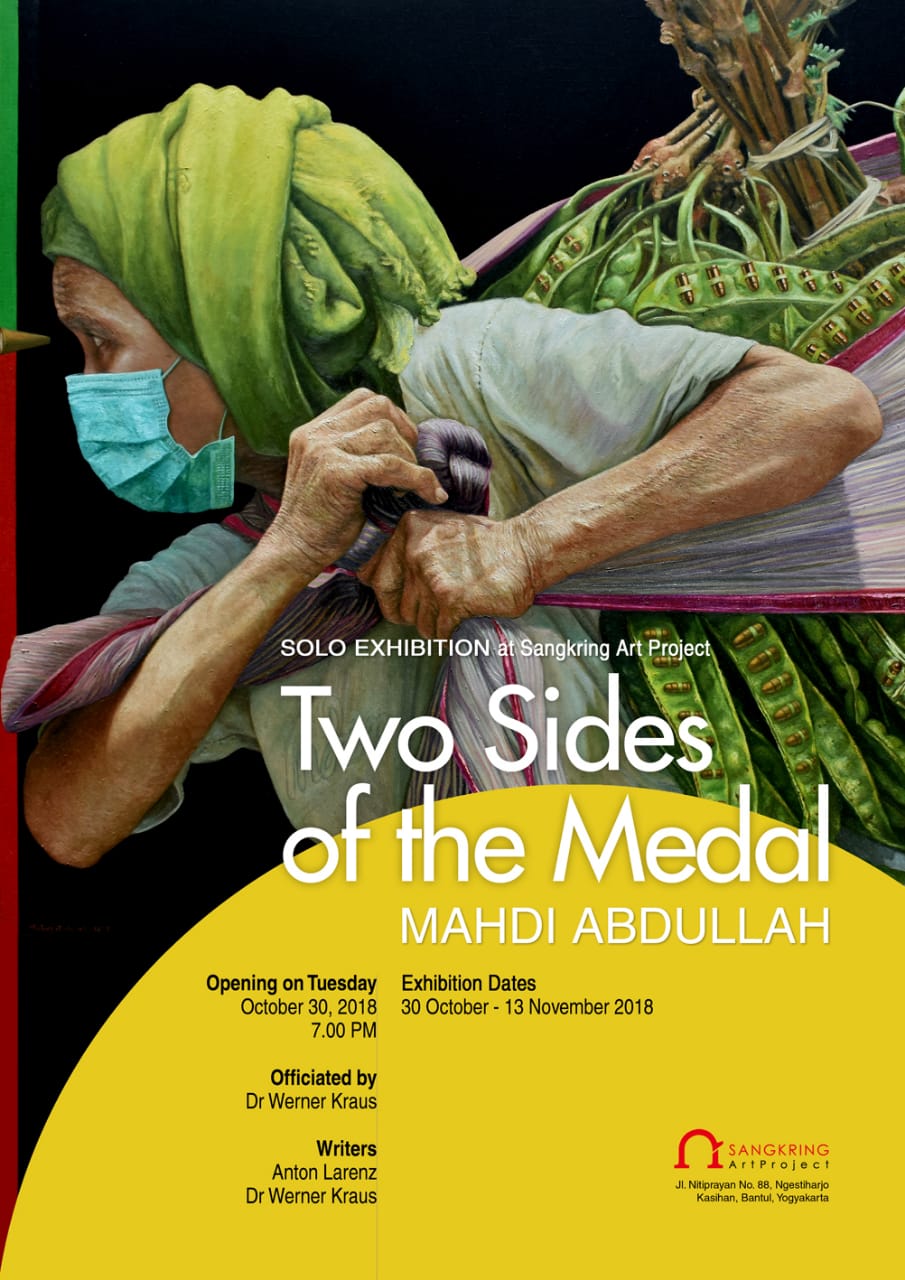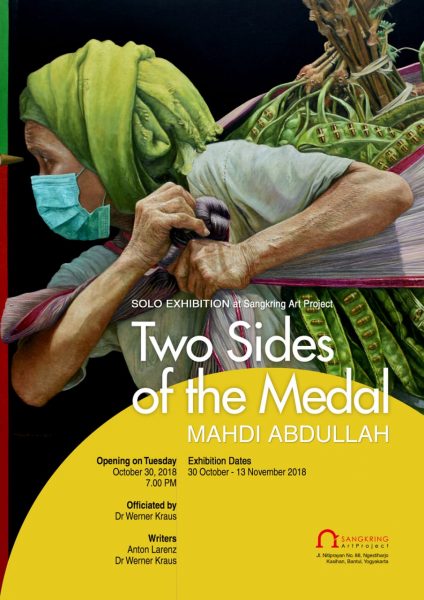[Pameran] Perupamuda #3 “Ring Road”



Youthquake
Menyoal pemuda memang tidak ada habisnya, terlebih soal frasa klise “pemuda adalah agen perubahan” di mana hingga hari ini masih mampu menunjukkan tajinya. Pada 2017 lalu, Oxford Dictionary mengukuhkan terma “Youthquake” sebagai word of the year. Terma tersebut bukanlah hal baru, mengingat Diana Vreeland pernah mengemukakannya melalui majalah asuhannya, Vogue, pada 1965. Jika Diana Vreeland menggambarkan youthquake sebagai kebangkitan budaya pemuda di London yang terjadi pada 1960-an, terutama dalam cara berpakaian, maka Oxford Dictionary menjabarkannya lebih luas. Yakni mengacu pada perubahan budaya, politik, atau perubahan sosial yang signifikan karena aksi atau pengaruh dari pemuda. Hal ini menandakan bahwa pemuda memiliki peran dan caranya masing-masing untuk mendayagunakan energinya merespon geliat zaman atau bahkan menciptakan maknanya sendiri.
Para pemuda masa kini itu dikelompokkan dan diberi nama generasi milenial oleh generasi sebelumnya. Menjadi rahasia umum jika generasi milenial dilabeli hal-hal negatif seperti individualis, apatis, pemalas, dan lain-lain. Namun, ketika Oxford Dictionary memberikan sorotan terhadap terma youthquake, setidaknya sedikit banyak mematahkan label-label yang menempel pada generasi milenial. Hal ini, salah satunya, didasari pada meningkatnya jumlah keikutsertaan pemilih muda di UK dan New Zealand yang mendukung partai oposisi.
Bisa jadi, hal ini pula yang mendorong para capres dan cawapres di Indonesia berlomba-lomba menjadi yang paling mewakili milenial. Daripadanya, menarik kemudian untuk menelisik kembali bagaimana praktik generasi millenial di Indonesia hari ini. Terutama, ketika generasi ini tidak mengalami perang dunia, revolusi, maupun reformasi namun mengalami perubahan zaman bernama kemajuan teknologi informatika.
Satu hal yang perlu menjadi catatan ialah, bahwa menyoal generasi tidaklah mungkin untuk digeneralisir. Meski kemajuan teknologi menjadi payung besar pengaruh sosio-historis generasi milenial, lantas tidak dengan begitu saja menihilkan order di mana mereka mengada. Misalnya, generasi milenial yang lebih sering mendiskusikan ihwal kritis akan berbeda dengan milenial yang mengikuti akademi kepolisian akan jauh berbeda ketika merespon isu-isu kenegaraan. Bukan berarti bahwa yang satu lebih baik dari lainnya, melainkan terdapat perbedaan daya cerap dan mengaktualisasikan diri berdasarkan arena di mana mereka berada.
Para muda di ranah seni rupa, misalnya. Hari ini memang jarang sekali yang menyoal isu kenegaraan atau bahkan menawarkan gagasan-gagasan segar. Jim Supangkat secara implisit dalam sebuah wawancara untuk pameran Manifesto “Multipolar”, mengatakan bahwa seniman hari ini tidak jauh beda dengan wartawan yang memberitakan sebuah realitas melalui produksi visual. Tetapi toh, seperti disebut dalam paragraf sebelumnya, generasi milenial hari ini tidak mengalami gejolak konflik yang konfrontatif seperti generasi sebelumnya.
Lingkar Perupa Muda
Pameran Perupamuda kembali digelar untuk yang ke-3. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan ruang Bale Banjar Sangkring sebagai salah satu upaya mendistribusikan kerja-kerja yang bersifat edukatif dan partisipatif. Program Perupamuda merupakan kesempatan dalam membuka ruang inisiasi dan kolaborasi antara galeri Sangkring dengan anak-anak muda. Pameran ini, seluruhnya diorganisir oleh anak muda, mereka punya hak penuh dari konsep hingga eksekusi sesuai dengan pertimbangan dan kesepakatan kolektif.
Menyimak peristiwa yang berhasil terselenggara sebelumnya, ada upaya panitia dalam meletakkan atau menegaskan kembali terkait prinsip, perspektif, konsep, pemahaman, mengenai perupa muda dan seni kontemporer sesuai dengan konteks di mana peristiwa itu digelar, yang setidaknya menjadi tawaran medan untuk dinegosiasikan bersama subjek yang berkepentingan secara terbuka. Masih dalam wacana kontemporer, setidaknya, tiga kali penyelenggaraan Perupamuda, ada pembacaan ulang mengenai medium karya yang terikat secara tema, misal pameran yang pertama fokus mengenai karya kanvas, kedua kertas, lalu yang ketiga ragam media.
Pameran ini mengambil tajuk “Ring Road”, judul ini sengaja dipilih dengan maksud memberi kesempatan bagi seniman muda secara lebih luas, semacam pemekaran wilayah untuk menjangkau berbagai medan dan disiplin seni rupa. Terkhusus di Yogyakarya, sebab hanya dalam areal yang dilingkari jalan utama saja, bisa menawarkan begitu banyak model kesenian. Dimaksudkan para muda-mudi yang turut berpartisipasi dapat secara bersama-sama membuat lingkaran besar, sekaligus jalan, sebagai kekuatan generasi muda. Perihal mengenai lingkaran, lebih lanjut bisa menjadi simbol atas kebersamaan dan persatuan.
Sebab generasi kini, dengan fasilitas akses informasi yang melimpah justru rentan terpecah belah oleh sebab sajian konten yang provokatif, misal seperti terjadi dalam perang medsos. Maka pameran, dengan kemungkinan aktivitas dan interaksinya secara komunal, dapat memberi ikatan yang lebih intim dan manusiawi. Pameran Ring Road bisa menjadi ruang sosial dan distribusi nilai dan makna antar pemuda, juga sebagai upaya konkrit dalam membedah bias dunia virtual yang menjadi bagian identifikasi para milenial.
Beberapa karya memiliki kemiripan satu sama lain seperti kehadiran warna-warna fosfor, bisa dijumpai dalam karya Aldi Wahyu, Kadek Suardana, Tahta Gilang, Ricky Qaliby dan Yula Setyowidi, yang seolah butuh wahana tersendiri untuk menempatkannya. Karya-karya ini membutuhkan jangkauan ruang tertentu, misal pengaturan cahaya relatif. Karya Suardana menempatkan gambar tradisional Bali yang telah digubah menjadi semacam latar namun juga ornamen. Latar ini seolah hadir dan hilang dalam lanskap alam natural tanpa kehadiran manusia. Suardana seolah ingin melukiskan, bahwa tradisi hadir selaras dengan alam, karyanya sebagai ungkapan harmonis antara spirit alam dengan tradisi.
Satuan panel-panel, baik dalam satu media utuh dan terpisah, hendak membangun narasinya tersendiri, seperti terdapat dalam karya Amri Cahya, Iwan Santika, Pradani Ratna, Taufiq HT, Ungky Prasetyo, Raka Hadi dan Roy Adhitama. Khusus karya kolaborasi Amri Cahya dan Janur Kilat bertolak dari permainan ular tangga. Ular tangga, yang bisa diasosiasikan sebagai perjalanan, perjuangan, nasib… ditampilkan secara menyenangkan lewat aktivitas berkebun. Bagi mereka, berkebun itu merupakan hal yang menyenangkan, membuat rileks saraf-saraf yang mulai menegang. Salah satu alternatif kegiatan untuk melepas penat. Dalam berkebun, lewat karya, sesungguhnya menyiratkan kemandirian, dan kebahagiaan atas interaksi langsung dengan alam. Sebagaimana hadir dalam karyanya, tak hanya suka ria memanen hasil kebun, namun juga mendapat kebahagiaan hakiki berupa cinta.
Adapun yang terus dan terus dilakukan dan mungkin selalu dirayakan adalah eksplorasi mengenai figur-figur rekaan, terlihat dalam karya milik Fika Ariestya, Diky Prasetyo, Wayan Sudarsana, dan Diana Puspita. Pada karya Sudarsana, Evolusi Alam, adalah gambar tentang keberlangsungan alam, masa depan yang ia cemaskan oleh sebab perubahan lingkungan yang tidak berpihak pada hari esok. Hewan, manusia, dan tumbuhan, ia gubah dalam satu subjek utuh, sebagai penegasan bahwa idealnya, sesama makhluk alam memiliki hak yang sama untuk hidup dan keberlangsungannya. Saya menganggap bahwa proses menghadirkan figur-figur baru, yang mungkin akan terus-menerus dilangsungkan tiap generasi, sebagai hasrat mencari pengalaman baru, dan juga secara tegas selalu menyampaikan muatan keberbedaan. Bahwa yang berbeda harus ditegaskan, namun dengan berbeda bukan berarti tidak bisa bersatu. Sayang, sepanjang sejarah, sebagaimana banyak kita tahu, perbedaan senantiasa menjadi alasan permusuhan. Tidakkah dunia ini mencoba kesempatan untuk berdamai?
Sifat dan sikap individual, seperti dialami pada kebanyakan generasi milenial hari ini, mungkin telah menjadi bagian dari karakteristik anak zaman yang tak bisa terelakkan. Perkembangan teknologi dan informasi terutama, telah menancapkan sistem dan gaya hidup yang khas. Berbagai kebutuhan hidup dapat, dan mungkin wajib terakomodir dalam media-media yang lebih bersifat artifisial. Alih-alih mengelak jadi tertinggal sementara ikut jadi terjerumus. Di zaman ini, hidup semakin lebih terasa untuk memilih dan menjalani risiko, kita hanya memiliki alternatif dalam menjalankan pilihan-pilihan yang tidak diinginkan, dengan bahasa lain yang cukup melegakan yaitu ‘memanfaatkannya’, seperti memanfaatkan medsos untuk berjejaring atau mempromosikan karya contohnya.
Angkatan muda, sejumlah 52 perupa yang terlibat dalam pameran ini, bisa jadi menandakan generasi seni rupa yang tidak diwarnai dengan perdebatan sengit dan terbuka, sikap kritis, juga terobsesi pada gerakan tertentu. Kita tahu bahwa sejarah seni rupa Indonesia dibentuk dari perdebatan-perdebatan yang melahirkan berbagai angkatan. Apakah ini sebuah kemunduran? Seperti sering dituduhkan oleh generasi sebelumnya, atau jangan-jangan ini merupakan sikap perupa muda untuk menolak model-model legitimasi generasi. Tak hanya Supangkat yang menganggap tiada perubahan berarti, laman histography.io juga tidak mencatat adanya karya seni penting sejak dirampungkannya patung Cristo de la Concordia pada tahun 1994.
Saya melihat bahwa semakin lunturnya peran tunggal pada medan, ruang, komunitas, atau peristiwa tertentu yang sebelumnya memiliki kuasa penuh dalam menjalankan atau menentukan arah perkembangan seni rupa, menjadikan semakin sulit dalam membaca generasi. Tetapi mungkin, justru kondisi ini memicu sikap kritis dalam perlu atau tidaknya, dan bagaimana mencatat generasi. Perubahan ini tentu banyak dipengaruhi perkembangan teknologi informasi, di mana setiap seniman kini bebas mengakses dan menjadikan dirinya sebagai subjek dimanapun ia ingin berada sesuai pilihan. Karya-karya yang berhasil dipamerkan dalam kesempatan ini kebanyakan merupakan narasi personal yang memuat dialektika perupa dengan dunia global yang dihadapinya.
Dalam buku populer khas generasi milenial “Sebuah Seni Bersikap Bodo Amat” karya Mark Manson, dikatakan bahwa, “Dalam hidup ini, kita hanya punya kepedulian dalam jumlah yang terbatas. Makanya, Anda harus bijaksana dalam menentukan kepedulian Anda.” Kunci untuk kehidupan yang baik, bukan tentang memedulikan lebih banyak hal; tapi tentang memedulikan hal yang sederhana saja, hanya peduli tentang apa yang benar dan mendesak dan penting. Tanpa berlebihan menggapai cita-cita besar yang menjadi keinginan orang banyak, sikap perupa muda dalam pameran “Ring Road” ini menjadi bermakna oleh karena dapat melakukan hal yang sederhana dan konkrit. Dengan membuat lingkaran kecil melalui pameran bersama justru menjadi kontribusi penting sebagai pemuda, sebab di waktu yang bersamaan, banyak anak muda tidak melakukan apa-apa.
Huhum Hambilly
Yogyakarta, 2 November 2018