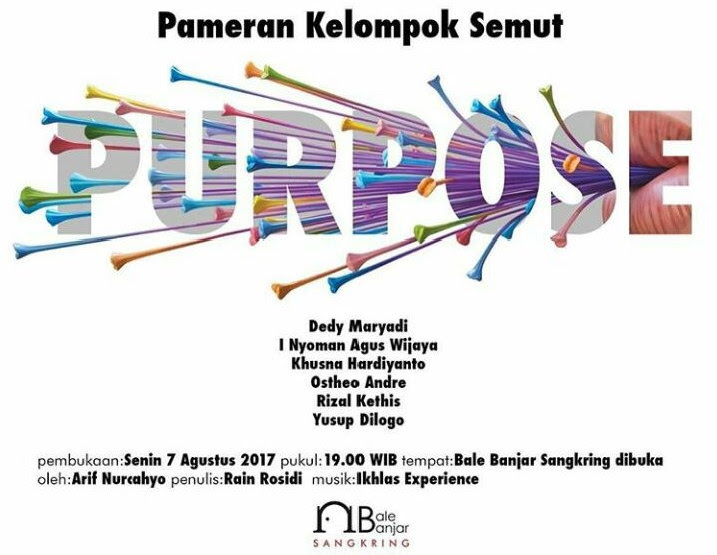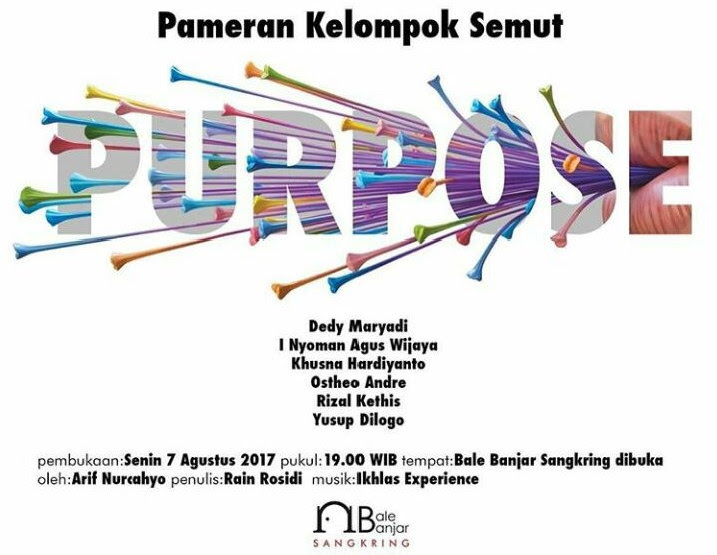April 30, 2018
In
Exhibitions

Yogya Annual Art #3 2018
Positioning
Sangkring Art
Jl. Nitiprayan no. 88, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
Opening: 6 May 2018, Start 7pm
Exhibition at Sangkring Art Space – Sangkring Art Project – Bale Banjar Sangkring – Lorong Sangkring – Wall Art – Outdoor Area
Officiated by: Ridwan Muljosudarmo
Writer:
Kris Budiman, Huhum Hambilly, Apriadi Ujiarso, Alit Ambara, Dwi S. Wibowo, Yaksa Agus
Info: @yogya_annual_art / @sangkringart
www.sangkringart.com
#sangkringart #yogyaannualart
Pameran Yogya Annual Art #3 “Positioning” di Sangkring Art
Pada kurun waktu 6 sampai 31 Mei 2018, Sangkring Art bermaksud menggelar pameran seni tahunan “Yogya Annual Art” yang ke-3 dengan tajuk “Positioning”. Yogya Annual Art adalah pameran seni 2 dimensional yang menitikberatkan pada seni lukis sebagai laporan perkembangan seni lukis Yogyakarta Indonesia mutakhir. Tajuk “Positioning” sengaja dipilih sebagai upaya penempatan diri yang tepat dan strategis demi membuat penonton terpikat sekaligus terikat. Hal ini juga sebagai kelanjutan atas gelaran sebelumnya, yaitu “Niat” dan “Bergerak”. Bagi Panitia YAA, lewat tema yang diusung, pameran bermaksud mempresentasikan proses yang merupakan dasar-dasar bertindak dengan tujuan membuat gerakan ke arah yang yang benar.
Pameran diadakan di tiga galeri sekaligus, Sangkring Art Space, Sangkring Art Project dan Bale Banjar Sangkring dengan melibatkan sekitar 90 an seniman. Adapun ruang-ruang lain di areal Sangkring yang juga menjadi bagian dari YAA, seperti Lorong Sangkring, Tembok Galeri dan Halaman di sekitar Sangkring. Tak lupa, sebagaimana tradisi dalam tiap pergelaran YAA, yaitu mengundang ‘seniman kehormatan’ untuk menampilkan karyanya di dinding suci. Pada kesempatan ini YAA menghadirkan karya dari tokoh dan akademisi Nyoman Gunarsa. Sosok Nyoman Gunarsa sengaja dipilih oleh sebab ia dikenal sebagai dosen yang sangat inspiratif dengan aneka provokasi unik yang mampu mengikat mahasiswa, dia adalah perupa yang pandai melakukan positioning yang tepat sekaligus strategis lewat karyanya yang memukau.
Sangkring Art Space
Di manakah posisi subjek dalam wacana? Dengan pertanyaan yang senada, dapat disimak pada karya-karya para perupa yang tengah digelar sekali ini di Sangkring Art Space. Bila karya-karya ini memproduksi pengetahuan (dan kuasa sekaligus), lalu di manakah posisi subjek pembaca atau penonton (audiens) di dalamnya? Pertama, tentu saja karya-karya ini memosisikan subjek-subjek yang selalu sudah tersubjeksi (subjected), terkondisi oleh konvensi dan tradisi genre masing-masing, yang sesungguhnya dalam setiap momen sejarah terus mengalami pergeseran dan pergesekan. Untuk sementara problem ini bisa kita tangguhkan dulu demi menengok posisi subjek yang kedua, yaitu penonton. Posisi subjek ini niscaya tak lepas pula dari jalinan kuasa/pengetahuan, sebab apa yang kita sebut sebagai penonton di sini hanyalah salah satu partisipan yang direpresentasikan (represented participant) oleh wacana. (Kris Budiman)
Sangkring Art Project
Menarasikan perupa muda hari ini yang pula berpredikat sebagai generasi milennial, menjadi ihwal cukup rumit dalam artian perlu banyak pertimbangan untuk menyiasatinya. Pola-pola lama guna ditasbihkan sebagai seniman seolah bukan jalan satu-satunya yang harus ditempuh. Internet mampu menjadi jalan tikus bagi perupa muda, di mana tentu saja konsekuensi tetap membayangi. Dengan kata lain, modal sosial semakin mudah diakumulasikan melalui jejaring yang aksesibel bagi para perupa muda, namun belum tentu dengan modal kultural guna menyematkan nilai simbolis melalui karyanya. Tetapi toh, lagi-lagi, para perupa muda ini sedang dalam masa inkubasi, di mana mereka sedang dalam proses menjadi yang merupakan jalan panjang. (Huhum Hambilly)
Bale Banjar Sangkring
Sepertinya tema positioning tidak menyentuh intensi personal tiga puluh lima perupa itu. Melalui garis dan warna tampak bahwa intensi karya terletak pada hasrat berbagi pengalaman dan pemikiran visual yang bernilai kepada publik seni. Beberapa karya menyatakan seni rupa abad ke – 21 makin kompleks. Periodisasi sejarah seni rupa perlu dipikir ulang, sebab di antara masa lalu dan masa kini, ada memori yang barusan berlalu yang patut dikenang secara visual. Seturut ruang penghayatan yang terbina, netralitas dan pemihakan dipertanyakan. Beberapa perupa memilih mematangkan gaya realisme, sebagian berkutat menyoal konsep. Lainnya melakukan eksperimen warna, dengan tujuan mendapat aspek pewarnaan yang keluar dari rumusan industrial. Pada arah lain berlangsung berbagai eksplorasi bentuk sebagai menu utama kekaryaan, baik ekspresif atau yang impresif. Terdapat pula eksplorasi naratif, yang tampaknya perlu pencermatan agar terjadi titik temu perspektif dan rasa yang lebih puitis. Menariknya beberapa perupa mengolah unsur air sebagai aspek penting dalam karya visualnya. Diambilnya kembali teknik – teknik tradisi, baik diterapkan pada garis atau pada warna, sungguh memperkaya pergerakan seni rupa Indonesia. Penuh dengan eunoia, pikiran yang baik; pemikiran yang indah disalurkan lewat garis dan warna. Tak berlebih bila di Bale Banjar Sangkring pada YAA #3 ini, publik seni melihat beragam karya lukis dengan karakter individual yang mantap. Hal ini tentu saja menggembirakan. (Apriadi Ujiarso)
Lorong Sangkring
Bikin poster itu gampang, semua orang bisa bikin poster. Poster mudah dibuat dan didistribusikan. Atraktif, platform yang mudah diakses untuk menyatakan pikiran, melibatkan orang dalam perdebatan, menciptakan diskusi yang dapat melintasi segenap spektrum masyarakat. Poster digunakan sebagai metode expresi sosial politik dan budaya. Sejak 2009 Alit Ambara secara intensif menggunakan poster untuk merespon isu-isu sosial-politik dan expresi personal. Dibawah label Nobodycorp. Internationale Unlimited sebuah inisiatif yang bertujuan mendorong diskursus serius tentang sosial atau sosial-politik melalui poster. Ia menggunakan setiap saluran media sosial yang tersedia di internet. (Alit Ambara)
Outdoor Area
Ada beberapa hal yang menarik untuk dilihat pada sejumlah karya mereka, terutama pada penempatan posisinya dalam merespon ruang. Berada di antara tiga bangunan yang demikian megah, tentu tidak mudah bagi karya-karya tersebut untuk menarik perhatian jika tidak disiasati dengan ukuran yang besar dan massif, ataupun pemilihan warna yang mencolok. Dari sini, kita dapat melihat bagaimana para pematung yang masih relatif muda ini begitu tanggap dan luwes dalam menempatkan karyanya. Selain itu, keenam pematung juga mengolah konsep yang hampir senada, sehingga memudahkan pemirsa untuk memahami masing-masing karya sebagai sebuah kesatuan yang saling terhubung satu sama lain. (Dwi S Wibowo)
Wall Art
Rujiman hadir dengan karya yang berjudul Koi Mili Gaya, dimana ikan –ikan koi ini bergerak , mengalir mengikuti arus dan dengan percaya diri untuk tebar pesona. Ikan Koi sebenarnya berasal dari Jepang, dipercaya membawa keberuntungan dan menjadi simbol harapan kesehatan dan kemakmuran. Bagi para Samurai, koi adalah simbol keberanian dan usaha pantang menyerah. Melalui Koi yang bergerombol bersama-sama meraih posisi ini, seolah-olah kita diajak untuk membaca dan memaknai tanda-tanda yang sesungguhnya sering tampak dalam dunia nyata, namun sering juga tidak kita sadari dan memaknainya.
Tepat diseberang karya Rujiman ada seorang perupa muda Yogi Septifano (OGGZ) dan Regian Hilarius (REX) ia menghadirkan karya Street Art dengan merespon luar ruang (outdoor). Mereka berdua berkolaborasi merespon dinding dengan 41 plat besi yang diikat dalam tajuk “One way /Satu arah”, yang bermakna satu jalan/jalur untuk melihat suatu pameran–dimulai dari Sangkring Art Space menuju Sangkring Art Project, dan menuju Bale Banjar Sangkring. Di situ akan menjadi jalur padat karena banyaknya tamu yang datang dan pulang melalui satu jalan, satu arah akan menjadi dua arah. (Yaksa Agus)