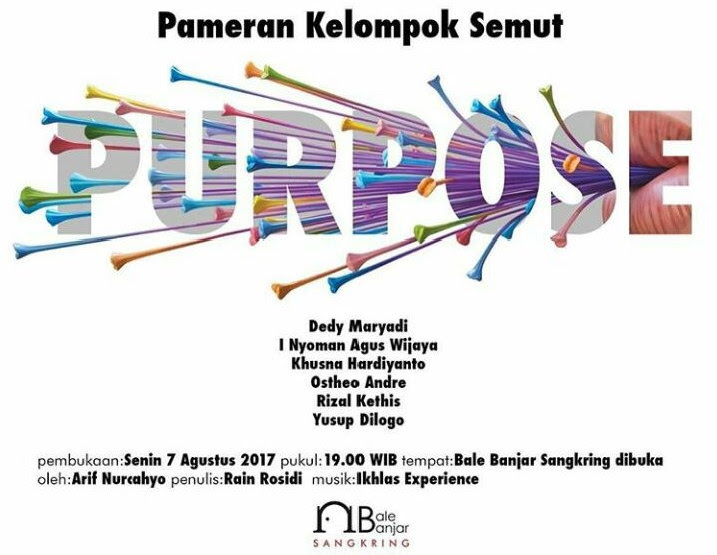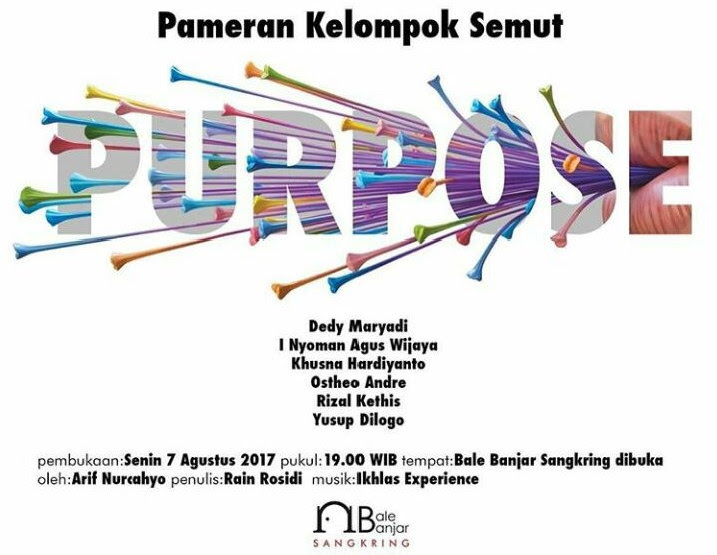August 11, 2017
In
Exhibitions

Permainan (dan) Selera
Oleh Ida Fitri
Seri Pameran Adu Domba a la Sangkring Art Space telah memasuki putaran yang ke-6. Perlu menarik ingatan kembali bahwa perhelatan ini merupakan simulasi –meniru situasi adu domba, untuk mengetengahkan dua perupa dalam satu arena pameran. Karena bukan kompetisi, maka kemampuan teknis dan ketajaman konsep yang diadu bukan untuk memunculkan pemenang dan menyingkirkan yang kalah, melainkan untuk memberikan kondisi bagi seniman untuk siaga berkarya dan siap berwacana.
Pameran Adu Domba seri ke-6 menampilkan lukisan-lukisan Yaksa Agus dan Luddy Astaghis, dua perupa yang berbeda gaya melukis (how to say) dan berbeda penggunaan bahasa visualnya untuk menyampaikan pesan (what to say). Namun keduanya sama sepakat bahwa karya rupa tak bisa berdiri sendiri tanpa konteks sosial atau imun dari problematika kehidupan sehari-hari.
Yaksa:
Berpijak dari ajaran Jawa dari R.M. Panji Sosrokartono “menang tanpa ngasorake”, bahwa kontestasi bukan sekedar perkara menang dan kalah, tetapi hendaknya juga menghidupi moralitas tentang bagaimana bersikap ksatria, jika menang maka tidak untuk merendahkan yang kalah. Untuk itu Yaksa lebih memilih dam-daman sebagai wahana kontestasi dalam karya-karyanya kali ini ketimbang jenis permainan tradisional yang lain.
Berbeda dengan catur, permainan yang dalam bahasa lain dikenal sebagai bas-basan atau checker ini, mengalahkan lawan dengan lebih santun. Tujuannya tidak untuk menyingkirkan lawan demi mendapatkan posisi atau ruang yang diinginkan, tetapi mesti cerdik dengan melampauinya. Demikian moralitas yang diajarkan dalam permainan tradisional ini, dan begitu pula pesan yang ingin disampaikan oleh Yaksa dalam lukisan-lukisan akrilik di atas kanvasnya. Ia membuatnya dalam dua sekuel yang masing-masing terdiri dari tiga panil. Seri pertama berjudul “Kopi Darat” yang masing-masing berukuran 100 Cm X 310 Cm. Tiga panil ini merupakan gambaran ruang interaksinya bersama Goenawan Mohamad, yang ditampilkan sebagai pria berbaju dan bercelana putih sedang duduk menghadap ke arah pembaca lukisan, dan di sampingnya tergelar papan dam-daman. Di ujung yang lain dari papan permainan tampak Yaksa sendiri sebagai lawannya. Pada suatu kesempatan GM –demikian sebutannya, pernah mengatakan bahwa jika dengan menggambar dan berpameran tidak laku maka ia akan kembali menulis. Pernyataan ini memberikan ide untuk berseloroh tentang dirinya, bahwa menulis itu sebagian ekspresi saja, sedangkan menulis dan melukis, keduanya sama-sama dilakukan.
Tiga lukisan dengan judul yang sama “Kopi Cangkir Blirik”, masing-masing berdimensi 145 Cm X 100 Cm, menjadi gambar permainan dam-daman Yaksa dengan tokoh seni rupa lainnya di Yogyakarta. “Kopi Cangkir Blirik #1” melawan Djoko Pekik yang lukisannya berjudul “Hari Pahlawan 10 November” dibuat tahun 2014 menjadi pemantik ide mengangkat dam-daman ke dalam Adu Domba #6. Sedangkan “Kopi Cangkir Blirik #2 merupakan momen ia melawan Heri Dono yang hanya terlihat gestur tubuh bagian belakangnya saja. Nasirun pun dilawannya di lukisan “Kopi Cangkir Blirik #3”. Ketiga seri ini merepresentasikan arena seni rupa Indonesia, di mana seorang perupa berkontestasi dengan perupa yang lain. Namun dari sekian banyak macam jenis kontestasi, Yaksa memilih karakter dam-daman, alih-alih pertandingan catur, sebagai metafora.
Di permainan dam-daman, setiap bidak menempati kedudukan dan menggenggam hak yang sama, tidak seperti biji-biji catur yang berperan dengan susunan hierarkis yang kedudukannya menentukan pola langkah tertentu. Dengan semangat egaliter, setiap orang atau bidak hanya bisa melangkah satu langkah saja, yaitu maju, mundur, kiri, kanan, atau serong sesuai dengan garis jalannya. Ada kesempatan menyingkirkan atau memakan musuh, namun tidak secara langsung. Hanya bisa melompati atau melewati tanpa merebut kedudukannya.
Yaksa mengasumsikan dirinya sebagai bidak di papan dam-daman yang bergerak melompati bidak lawannya untuk menang. Sebagai seniman, ia tak perlu menempati posisi perupa lain dengan cara menjatuhkan. Setiap perupa hanya perlu strategi yang terukur untuk melampaui perupa lainnya, bukan menyingkirkannya dari posisi yang telah diperjuangkan.
“Kopi Hari Ini” berukuran 140 Cm X 100 Cm dengan medium cat akrilik di atas kanvas, merupakan karya yang berbeda namun menampilkan satu subyek yang hadir di seluruh karya Yaksa, yaitu kopi. Secangkir kopi dianggap sebagai alat strategi sosial yang lunak di tengah papan percaturan hidup yang makin keras. Karena, secangkir kopi selalu layak mendampingi pertemuan-pertemuan, yang menghubungkan diri dengan orang lain, di ruang tamu, angkringan, pos ronda, café, di manapun. “Pertemuan” 145 Cm X 180 Cm merupakan deskripsi dari keterhubungan satu manusia dengan manusia lain tersebut untuk membentuk ikatan sosial.
Yaksa Agus, pelukis cum penulis dan kurator seni rupa ini memanisfestasikan wacana yang penting dalam situasi politik, ekonomi dan sosial saat sekarang ini ke dalam gaya melukis yang segar dan cenderung bermain-main. Di saat strategi licik penuh tipu daya menjadi panglima, dan upaya mengaburkan kebenaran dengan wacana yang seolah benar diviralkan tak terbendung, Yaksa menawarkan strategi bermain di arena sosial secara santun, yang bisa diinisiasi kembali dari permainan tradisional dam-daman.
Luddy Astaghis
Tiga seri panil masing-masing berukuran 37 Cm X 129,5 Cm dengan cat akrilik di atas kanvas berjudul “Kamu Suka Yang Mana?” merupakan pertanyaan sekaligus tawaran Luddy sebagai pelukis kepada para penikmat seni untuk mempersoalkan selera. Pria yang pernah menerima penghargaan Pratisara Affandi Adi Karya Yogyakarta dan Indofood Art Award tahun 2002 ini membuat ketiga panil tersebut dengan narasi yang seolah berlapis-lapis. Seri “Kamu Suka Yang Mana” #1, terdiri dari tiga lapis narasi yaitu sepotong kepala ikan berkualitas fotografis, dua figur berhadapan berkarakter karikatur dan lapis ketiga berupa lukisan monokrom biru sebagai latar. “Kamu Suka Yang Mana” #2 merupakan tiga lapis kesatuan antara ayam panggang tampak seperti foto, dua figur karikatur dan latar berwarna monokrom salem. Sementara yang terakhir “Kamu Suka Yang Mana” #3 adalah rangkaian lapisan apel hijau, tiga orang figur dengan latar monokrom hijau.
Kepala ikan, ayam panggang dan apel hijau, masing-masing dimaksudkan oleh Luddy sebagai representasi simbolik dari selera. Dari sekian banyak hal tersedia, mengapa orang memilih yang berbeda dengan orang lain? Apa yang membuat selera satu orang dengan lainnya tidak sama? Mengapa Luddy menggunakan apel, ayam panggang dan kepala ikan sebagai preferensinya sendiri dari sekian banyak hal yang sebenarnya mampu mewakili wacana yang sedang diangkatnya, yaitu selera?
Studi tentang selera dan diskursus yang berkembang telah cukup tua dipelajari orang. Kant menyatakan bahwa selera adalah murni tanpa kepentingan dan tujuan, serta niscaya. Tetapi Bourdieu dalam surveinya yang panjang berhasil menganalisis bahwa selera, termasuk preferensi terhadap seni, dikonstruksi secara sosial dan merupakan produk adanya perbedaan kelas. Ia membedakan kelas selera tinggi atau aristokrat, dengan selera popular atau jelata. Kelas selera tinggi memandang dari aspek estetika semata yaitu bentuk dan perspektif, yang dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan. Sehingga ia berjarak dan meniadakan kondisi obyektifnya. Sedangkan selera populer atau jelata berkembang lebih alamiah akibat persentuhan obyek tersebut dengan kehidupan sehari-hari, sehingga lebih dibaca atau dipahami kualitas fungsinya ketimbang aspek dekorasinya.
Lebih jauh Bourdieu menyimpulkan bahwa selera merupakan relasi antara habitus, kapital dan arena sosial. Sehingga selera bukan sesuatu yang personal atau privat dan berorientasi pribadi, melainkan penanda orientasi sosial. Jika selera konsumsi seseorang menunjuk pada apel ketimbang ayam panggang dan ikan sebagai preferensi, maka sesungguhnya ia tidak sedang memilih secara bebas. Secara sederhana, pilihannya ini terbentuk dari produksi interaksi antara tiga hal tersebut: pola perilaku (habitus) tertentu, mungkin telah sejak lama mendapatkan manfaat mengkonsumsi apel bagi tubuh; kapital (sosial, budaya, ekonomi, politik) mungkin secara ekonomi mampu membeli; dan arena sosial di mana individu ini mungkin berada di lingkungan vegetarian.
Masih melanjutkan membincang selera, enam lukisan “Ingkung” berukuran 28 Cm X 29 Cm memberikan hanya satu pilihan saja, yaitu ayam ingkung tetapi dengan beragam warna. Abu-abu, kuning, fuchsia, hijau, salem, dan biru, mencolok mata karena berada di antara lukisan cat akrilik berwarna perak di atas kanvas. Bagi Luddy, ingkung atau ayam yang dimasak utuh seluruh badan itu sarat dengan muatan makna. Ia muncul setiap kali acara-acara penting digelar untuk mengungkapkan rasa syukur (Syukuran), mengharap keselamatan (Slametan), atau acara-acara baik lain yang biasa disebut Kenduri atau Kenduren. Setelah doa dipanjatkan, biasanya Ingkung dikepung peserta acara untuk dimakan bersama-sama. Hal ini dilihatnya sebagai simbol kebersamaan dan bisa mewakili selera semua golongan karena tak mengenal strata sosial. Dalam level ini, Luddy menyodorkan fakta lain, meskipun muncul ide untuk mengelompokkan orang-orang dengan selera yang sama –yaitu terhadap Ingkung, namun sesungguhnya preferensi setiap individu terhadap detail pun mustahil sama, entah rasa, warna, tekstur, aroma dan derajat perbedaan selera lainnya.
Di karyanyanya yang lain “Pecinta Ikan Koki” berukuran 145 Cm X 200 Cm menggunakan cat akrilik di atas kanvas, Luddy menggiring ke alam imajinasi. Ia melukis banyak hal di dalam satu bidang kanvas yang terbuka untuk diterjemahkan, teks-teks berupa subyek-subyek yang lepas menggugah para pembaca karyanya untuk mencoba menemukan sendiri kaitan-kaitannya dalam konteks yang melingkupi.
Dengan kompleksitas yang berkelindan seperti di atas, Luddy menggelitik kesadaran kita bahwa selera orang niscaya berbeda karena konstruksi sosial yang melatarinya pun berbeda. Dengan cara bagaimana kita akan melihat karya Luddy? Dengan selera tinggi atau rendah? Apakah kita akan membacanya dengan kacamata yang hanya melihat forma estetis (perspektif dan bentuk) atau mengapresiasi fungsinya sebagai bahasa ungkap realitas sosial yang ada di sekiling kita? Distingsi tinggi-rendah ini mungkin tak bisa kita abaikan, tapi kita tak harus tunduk padanya. Sebab kita bisa mengapresiasi karya Luddy secara tinggi dan rendah, dari forma estetis sekaligus fungsinya.